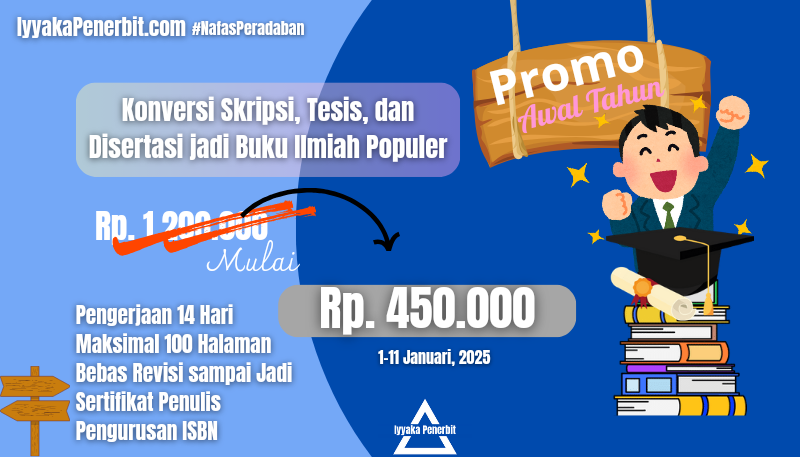(Direktur Eksekutif Maqasid Project)
Filsafat dan Hukum Islam: Penjelasan Konsep
Sudah menjadi keharusan dalam kajian filsafat,
bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah clarifiying concepts (memperjelas
konsep) (Faiz, 2021: 105). Konsep yang bersifat “laten” tentu membutuhkan
perangkat agar konsep itu termanifestasi dalam perundingan filsafat;
manifestasi konseptual disebut dengan term. Dengan kata lain, “term” mewujudkan
“konsep” itu dalam tataran rill bahasa (Maarif, 2016: 40).
Pada bagian pendahuluan ini, penulis akan menguraikan
lebih dahulu ihwal term filsafat, lalu disusul dengan pertanyaan bagaimana
konsepnya? Kemudian, menjelaskan term “hukum Islam”, disusul pula dengan
pertanyaan, bagaimana konsepnya?
Pertama, mengenai
“filsafat”. Penjelasan tentang term “filsafat” agaknya tak usah lagi dipanjang-panjangkan
pembahasannya pada bagian ini. Penulis sederhanakan saja definisinya sebagai
aktivitas, yakni ber-filsafat. Berfilsafat itu, berarti berpikir, berefleksi,
dan bermenung (kontemplasi) tentang “apa pun”, tujuannya adalah kebenaran dan
kebijaksanaan. Kalau orang mulai berfilsafat, dengan sendirinya akan mengerti:
apa itu filsafat?
Kedua, ihwal hukum
Islam. Saat ini, sudah banyak kepustakaan yang membahas mengenai term “hukum
Islam”, tapi hampir keseluruhannya mengatakan, bahwa sebenarnya term hukum
Islam tidak didapati “ekuivalensi-nya” dalam al-Quran dan al-Sunnah, serta
tidak dipakai secara operasional dalam pustaka Islam klasik (Nasution, dkk.,
2022: 21; Turnip, 2021: 2; Djamil, 1997: 11). Lalu, bagaimana menjelaskan
konsep hukum Islam?
Diakui secara jujur oleh para ahli hukum Islam
di Indonesia, memang sulit untuk memutuskan batasan makna dari hukum Islam
(Arfa & Nas, 2021: 43). Karena itu, untuk menyederhanakan, penulis mengutip
penjelasan M. Yasir Nasution (2010: 33), bahwa term hukum Islam mengandung
(memiliki konsep) pengertian yang sangat luas, “meliputi nilai-nilai (al-syariah);
norma-norma yang dikategorisasikan (al-hukm al-syar’iy); kaidah-kaidah
penerapan norma-norma itu (fiqh); dan perundang-undangan formal (qonun),
yang besumber dari al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw.”. Karena itu,
perundingan mengenai hukum Islam, berarti merundingkan keempat konsep tersebut,
atau sebagiannya saja.
Hubungan Filsafat dengan Hukum Islam
Sampai saat ini, secara tipologis, ada 3
(tiga) kelompok masyarakat muslim dalam kaitan penerimaan mereka terhadap filsafat
sebagai bagian studi hukum Islam. Pertama, kelompok muslim yang menolak
filsafat secara total; kedua, adalah kebalikan dari kelompok pertama,
yakni menerima filsafat secara total; dan ketiga, kelompok muslim yang
menerima filsafat secara kritis.
Mengenai kelompok pertama, yakni kelompok
muslim yang menolak filsafat secara total, berpandangan bahwa orang-orang yang
belajar filsafat sebagai ahl al-ahwa wa
al-bida’ (orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan pelaku bid’ah),
pendeknya golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Bukan tanpa alasan,
susunan argumen yang dipakai oleh pandangan yang menolak sepenuhnya filsafat
adalah karena istilah filsafat bukanlah berasal dari bahasa Arab. Tidak satupun
dalam pustaka Islam zaman salaf al-salih ditemukan istilah filsafat.
Kelompok pertama ini melanjutkan, bahwa pada kenyataannya
filsafat datang dari bangsa Yunani, bangsa yang dianggap sebagai penyembah dewa-dewa
mitologis. Sehingga filsafat adalah pemikiran asing yang bersumber dari luar
Islam dan kaum muslimin, harus ditolak sepenuhnya.
Sedangkan kelompok kedua, kebalikan dari
kelompok pertama, yakni menerima filsafat secara total. Pandangan kelompok ini
bermula dari argumen bahwa al-dina huwa al-‘aqlu wa la dina liman la ‘aqla
lah (agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal).
Filsafat yang selalu meluaskan peran akal seluas-luasnya, dianggap sangat
relevan dengan Islam berdasarkan konsideran tersebut. Dengan demikian, kelompok
ini selalu mengukur validitas dan kebenaran hukum Islam lewat pertimbangan akal
semata.
Selanjutnya, kelompok yang ketiga, yakni
kelompok muslim yang menerima filsafat secara kritis dalam hubungannya terhadap
studi Islam. Menerima secara kritis berarti kelompok yang sudah mampu memahami
perbedaan antara filsafat sebagai produk atau hasil berpikir filosofis
tertentu, yang berbeda dengan filsafat sebagai aktivitas berpikir, berefleksi,
dan bermenung (kontemplasi) tentang “apa pun”.
Memang, filsafat selalu berurusan dengan
manusia yang berpikir, dus berkaitan dengan produk pikiran dan aktivitas
berpikir manusia tersebut. Sebagai contoh, kita sering menemukan
istilah-istilah dalam dalam filsafat, seperti komunisme, sosialisme,
liberalisme, dan sebagainya. Bagi kelompok pertama, tentu aliran-aliran
(ideologi) semacam ini menjadi alasan mereka menolak filsafat, sebab
bertentangan dengan ajaran Islam. Sayangnya, kelompok pertama ini, mereduksi
filsafat sebagai produk pikiran semata, dan tidak mempertimbangkan filsafat
sebagai aktivitas berpikir. Sedangkan kelompok kedua, malah mencoba
merangkaikan istilah-istilah tersebut dengan Islam, kita sering mendengar atau
membaca istilah-istilah seperti Islam Liberal, Islam Sosialis dan sebagainya.
Adapun kelompok ketiga, tetap mengunakan filsafat, tapi sebagai aktivitas
berpikir; juga memperhatikan pikiran-pikiran yang sejalan dengan ajaran Islam
atau logika nubuwwah.
Kelompok ketiga ini, menggunakan filsafat
sebagai aktivitas berpikir namun tetap berpegang teguh pada al-Quran dan
al-Sunnah. Bahkan kelompok ketiga inilah yang telah berhasil mewariskan
“pikiran filosofis yang orisinal” sebagai pusaka umat muslim saat ini. Kelompok
ketiga inilah yang berhasil mendirikan bangunan filosofis hukum Islam yang
islami.
Konon dikatakan oleh sementara orientalis dan
beberapa sarjana barat, bahwa umat Islam tidak mempunyai filsafat (produk
berpikir filosofis). Filsuf-filsuf Muslim hanya menyalin, atau melakukan
plagiat dari filsafat Yunani. Pandangan
tersebut kemudian dibantah, setelah nyata garapan Muhammad Idris al-Syafi’i
dalam Al-Risalah—bidang ushul al-fiqh pertama yang dibukukan,
namun ada pendapat bahwa Ja’far al-Shadiq-lah yang pertama kali menuliskan ushul
al-fiqh (Jum’ah, 2017: 34). Al-Syafi’i, sebagaimana penjelasan Musthafa
Abdurraziq yang dikutip Hamka (2020: 39), adalah salah satu tokoh besar umat
Islam yang berhasil mempunyai filsafat yang tumbuh dalam Islam sendiri, yang
orisinal, dan bukan plagiat.
Telah diketahui, bahwa Al-Syafi’i merupakan
tokoh ternama dalam bidang hukum Islam. Karena itu, filsafat hukum Islam adalah
salah satu bangunan filsafat yang tumbuh dan berkembang dalam kajian Islam itu
sendiri, tidak membebek pada filsafat barat sebagaimana yang dituduhkan.
Untuk menjelaskan bangunan filosofis yang
ditawarkan al-Syafi’i tersebut, bukan di sini tempatnya. Bagi pembaca yang
sudah mengenal standar berpikir ala filsafat, silahkan rujuk langsung kepada
karya Al-Syafi’i yakni Al-Risalah. Buah pena Al-Syafi’i tersebut tidak
ditemukan acuannya dalam kajian filsafat mana pun, termasuk di Yunani sendiri,
artinya pikiran filosofis Al-Syafi’i tumbuh dan kembang dalam Islam itu
sendiri.
Alhasil, hubungan filsafat dengan hukum Islam
itu dapat dikatakan memiliki hubungan yang erat. Hubungan tersebut paralel
dengan hubungan Islam dan akal manusia. Maksudnya, hubungan filsafat (akal) dan
hukum Islam (agama) bukan soal porsi, tapi soal ketundukan: apakah akal yang
tunduk terhadap Islam, atau ajaran Islam yang harus tunduk terhadap akal?
Bagi muslim, tentu saja ketundukan terhadap ajaran Islam adalah bersifat mutlak, dus akal harus tunduk terhadap ajaran Islam. Namun, bukan berarti akal itu dimatikan, tetap gunakan akal seluas-luasnya dan berpikir sedalam-dalamnya dalam rangka memahami Islam, sehingga lahirlah hukum yang Islami. Boleh jadi, orang yang menolak filsafat (peran akal) dan mengaku tunduk pada Islam, malah berhukum secara serampangan atau tidak Islami. Sekali lagi, hubungan filsafat (akal) dan hukum Islam (agama) bukan soal porsi penggunaan, tapi soal ketundukan: Apakah Islam harus dipaksa tunduk terhadap akal manusia, atau akal-lah yang tunduk terhadap ajaran Islam?